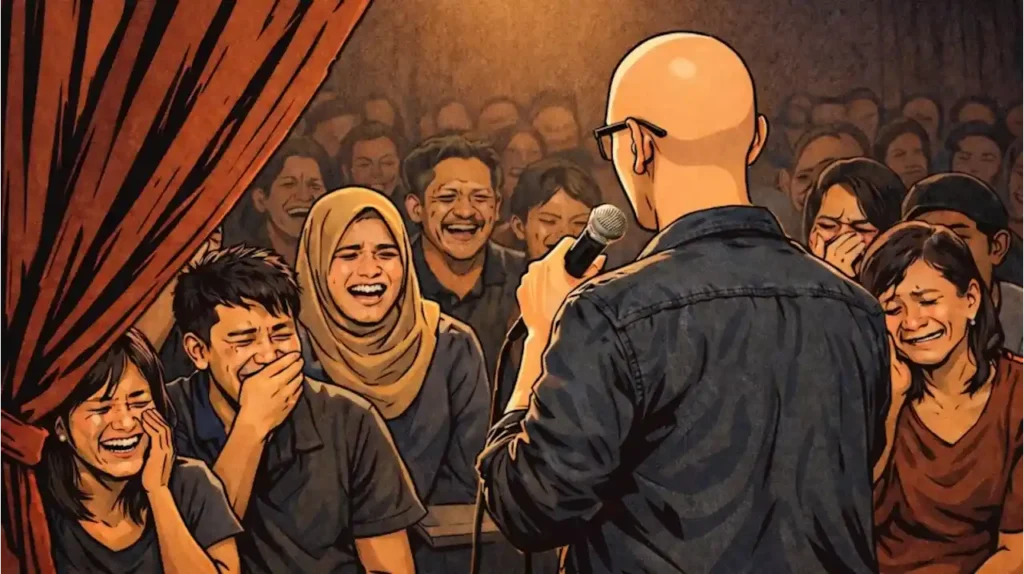Dalam perjalanan hidup, manusia seringkali terjebak dalam delusi kesempurnaan. Kita cenderung membangun benteng pertahanan diri (defensif) saat seseorang menunjukkan celah dalam pemikiran atau perilaku kita. Padahal, secara filosofis dan sosiologis, kritik adalah instrumen paling efektif untuk pertumbuhan. Kritik, jika diletakkan dalam proporsi yang tepat, bukanlah serangan personal, melainkan masukan konstruktif yang berfungsi sebagai cermin untuk melihat “noda” yang tidak bisa kita lihat sendiri.
Kritik adalah katalisator kemajuan. Tanpa kritik, seorang pemimpin akan menjadi diktator, seorang seniman akan menjadi stagnan, dan seorang manusia akan menjadi sombong. Kritik yang membangun (constructive criticism) memberikan perspektif baru yang seringkali luput dari pengamatan subjektif kita.
Dalam dunia profesional maupun personal, kesiapan untuk dikritik menunjukkan tingkat kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi. Orang yang siap dikritik adalah mereka yang telah selesai dengan egonya; mereka lebih mencintai kebenaran dan perbaikan daripada sekadar validasi kosong.
Fenomena “Mens Rea” Pandji Pragiwaksono dan Ujian Kedewasaan Berpendapat
Baru-baru ini, jagat media sosial di Indonesia ramai membicarakan potongan video komika Pandji Pragiwaksono terkait konsep Mens Rea (niat jahat) dalam konteks kritik terhadap kebijakan atau tokoh publik. Fenomena ini menarik untuk dibedah bukan hanya dari sisi hukum, tetapi dari sisi budaya kritik kita.
Pandji menekankan bahwa dalam mengkritik, seringkali yang dilihat adalah “cara” atau “diksi” yang digunakan, namun poin utamanya adalah apakah ada niat jahat (mens rea) untuk menjatuhkan karakter secara personal atau justru niat untuk memperbaiki keadaan. Namun, di sisi lain fenomena ini juga menunjukkan betapa rentannya masyarakat kita terhadap perbedaan pendapat. Ketika kritik dilontarkan, pihak yang dikritik seringkali langsung merasa terancam secara eksistensial.
Kasus ini mengajarkan kita dua hal:
Bagi Pemberi Kritik: Penting untuk menjaga agar kritik tidak bertransformasi menjadi penghinaan atau ad hominem. Niat yang baik harus dibungkus dengan cara yang juga baik agar pesan perbaikan bisa tersampaikan tanpa tertutup oleh kebisingan emosi.
Bagi Penerima Kritik: Kita perlu memiliki filter untuk memisahkan antara “cara penyampaian” dan “substansi kritik”. Jika substansinya benar, maka ego harus ditekan demi perbaikan bersama, terlepas dari apakah kita menyukai orang yang menyampaikannya atau tidak.
Kritik dalam Pandangan Islam: Tashih dan Nasihat
Islam tidak mengenal konsep manusia yang maksum (bebas dari dosa) kecuali para Nabi. Oleh karena itu, saling menasihati dan mengkritik adalah kewajiban agama untuk menjaga stabilitas moral dan sosial.
- Saling Menasihati dalam Kebenaran
Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ashr ayat 3:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 3)
Ayat ini menegaskan bahwa kerugian manusia hanya bisa dihindari jika mereka saling memberi masukan (tawaashau) demi kebenaran. Kritik dalam Islam disebut sebagai bagian dari dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar.
- Agama adalah Nasihat
Rasulullah SAW bersabda dengan tegas bahwa inti dari keberagamaan adalah kesediaan untuk menerima dan memberi masukan:
الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ
“Agama itu adalah nasihat.” (HR. Muslim)
Nasihat di sini bermakna keinginan baik bagi orang yang dinasihati. Jika kita menutup diri dari kritik, berarti kita menutup pintu agama dan perbaikan diri. Bahkan, Umar bin Khattab RA, salah satu pemimpin terbesar dalam Islam, pernah berkata: “Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aib-aibku kepadaku.” Ini adalah puncak dari mentalitas manusia yang siap dikritik: melihat kritik sebagai hadiah, bukan ancaman.
Mengelola Ego di Era Digital
Di era media sosial yang serba cepat, kritik seringkali datang dengan bahasa yang tajam dan tanpa filter. Fenomena Pandji Pragiwaksono dan perdebatan mens rea menunjukkan bahwa di ruang publik, niat dan cara penyampaian akan selalu berbenturan. Namun, sebagai pribadi yang merindukan kemajuan, kita harus mampu “memungut mutiara di dalam lumpur”.
Jika kritik itu datang dengan bahasa yang kasar namun contains truth (mengandung kebenaran), ambillah kebenarannya dan buang kasarnya. Jika kita hanya mau menerima kritik yang disampaikan dengan lemah lembut, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk belajar dari realitas yang pahit.
Kesiapan untuk dikritik adalah tanda kematangan jiwa. Kritik yang membangun adalah “obat” yang mungkin terasa pahit di lidah namun menyembuhkan penyakit dalam karakter kita. Fenomena mens rea mengingatkan kita bahwa niat dalam mengkritik itu penting, namun kelapangan dada dalam menerima kritik jauh lebih penting bagi pertumbuhan kolektif bangsa.
Sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, marilah kita jadikan kritik sebagai jembatan menuju perbaikan, bukan tembok pemisah. Manusia yang hebat bukanlah manusia yang tidak pernah salah, melainkan manusia yang selalu siap memperbaiki diri saat diingatkan. (*)